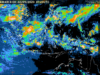Bu Tejo jadi bintang baru setelah Tilik ditayangkan perdana pada 17 Agustus 2020. Gratis pula di YouTube Ravacana Films. Praktis penonton dari berbagai kalangan dapat menikmatinya dan memberi reaksi beragam. Namun, Bu Tejo yang ceplas ceplos tetap menjadi sorotan.
Sejatinya, film pendek Tilik berdurasi 32 menit sudah dirilis pada 2018. Film Tilik meraih penghargaan Film Pendek Terpilih pada Piala Maya 2018, Official Selection Jogja-Netpac Asian Film Festival 2018, dan Official Selection World Cinema Amsterdam 2019. Setelah keliling di layar festival, barulah Tilik dilepas untuk dinikmati penonton Indonesia.
Ada cerita-cerita menarik ketika membicarakan soal Tilik. Ide cerita, nilai-nilai dalam film, hingga alasan menggunakan truk ketimbang bis untuk ibu-ibu yang hendak menjenguk bu lurah di rumah sakit. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi keresahan Wahyu Agung Prasetyo sebagai sutradara, yang dituangkan ke film Tilik?
Sutradara alumnus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini pun menyempatkan wawancara dan buka “dapur” seputar film Tilik dalam nuansa yang santai. Berikut perbincangan Medcom.id pada Kamis, 20 Agustus 2020 :
Bagaimana melihat antusiasme/reaksi penonton di media sosial terhadap film Tilik?
Speechless, sih, sebenarnya. Karena enggak menyangka sampai sebegininya, aslinya. Mensyukurilah, ternyata bisa sebegininya film pendek.
Awal viralnya dari mana, mas? Kan ini dua tahun lalu dirilis tetapi baru sekarang tetangkap radar penonton.
Sebenarnya kalau kami anak-anak independen, gitu, mbak, punya kultur ketika bikin film kami akan distribusi ke festival film dulu. Itu kenapa sempat menang di Piala Maya. Selama dua tahun itulah kami edarin di pemutaran festival sama pemutaran alternatif.
Nah, biasanya, kami punya kultur setelah dua tahun itu baru kami rilis di publik, entah media, platform online, dan sebagainya. Makanya, momentumnya kemarin pas 17 (Agustus) kami rilislah karena sudah dua tahun. Udahlah ini buat publik. Akhirnya, boom-nya di YouTube itu.
Cerita Tilik ini berangkat dari mana, mas?
Cerita ini itu muncul ketika dua tahun sebelum pembuatannya, aku, biasa anak-anak Jogja, nongkrong di angkringan terus ngobrol-ngobrol. Aku sama penulisnya (Bagus Sumartono) ngobrol, memang kami sering diskusi bareng. Nah, dia cerita sama aku kalau, “Aku habis lihat ibu-ibu pada naik truk tilik (menjenguk) orang sakit di salah satu rumah sakit dekat Malioboro”. Dia bilang kalau sebenarnya mereka itu bukan mau tiliknya, tapi mau ke Malioboro-nya, belanja.
Dari situlah aku terngiang-ngiang terus selama dua tahun itu sebelum akhirnya kami bikin film. Selama dua tahun itu, aku merasa resah terus aku merasa, aku sadar ketika saat itu aku mau bikin film ini. Ini effort-nya gede dan budget-nya besar. Kebetulan di Jogja ada program dari Dinas Kebudayaan DIY namanya Danais yaitu Dana Istimewa. Itu program bantuan buat para pelaku seni dan kami khususnya anak-anak seni. Akhirnya kami mencobalah propose ke situ, kami pitching dan Alhamdulillah kami dapat. Dikemaslah ceritanya dari berbagai macam.
Sebenarnya akhirnya, berangkatnya dari gini, aku, produser, sama penulis punya kesamaan yang sama yaitu memiliki ibu seorang janda. Nah, kesamaan inilah yang sebenarnya kami tarik dan kami narasikan begitu bahwa perempuan yang punya status single itu sering digunjing, sering diomongin banyak orang. Padahal orang-orang itu enggak tahu sebenarnya background story itu, asal nge-judge, lah.
Makanya, selama perjalanan di film itu ngomongin Si Dian yang punya status single ini. Walaupun di akhir aku punya statement bahwa sebenarnya perempuan yang berstatus single itu juga punya hak atas pilihan hidupnya sendiri. Jangan kalian nge-judge dalam waktu yang sangat singkat, sebelah mata doang.
Aku dapat kritikan banyak dari ending-nya, banyak diskusi-diskusi yang datang kenapa ending-nya harus begini? Dan aku selalu meng-counter balik, “Kamu beneran nonton filmnya enggak sebenarnya? Apa kamu jangan-jangan terhipnotis sama perannya Bu Tejo? Kok, kamu sampai se-pro itu”. Begitulah.
Saya nonton ending-nya trenyuh, mas. Saya juga menantikan benar enggak, sih, yang dibilang sama Bu Tejo, ending-nya gimana, tetapi ternyata Mbak Dian seperti itu. Menarik ketika Mas Wahyu bilang ini berangkat dari perspektif perempuan single atas pilihan hidupnya, tetapi yang saya tangkap di beberapa respons dari kebanyakan teman-teman, bukan kritikus, yaitu mereka yang menyambut positif, menganggapnya sebuah hiburan. Padahal, cerita di baliknya adalah sebenarnya kalau kita terlibat itu sangat pedih. Bisa dibilang ironi. Menurut Mas Wahyu, seperti apa isu ini sebenarnya terjadi sekarang dan bagaimana penonton Indonesia kita sekarang menangkap satu hal yang sebenarnya ironi sebagai humor?
Iya, betul. Mungkin itu juga salah satu value kenapa film ini bisa meledak karena ironi yang dihumorkan oleh mereka sendiri. Dan aku sepakat bahwa film ini sebenarnya ironi. Ironinya apa? Karena orang-orang yang bergerak di film itu memang menunjukkan hal-hal yang sangat miris. Orang-orang berkerudung, tetapi ngomongin orang, segala macam.
Nah, untuk ending-nya seperti itu sebenarnya kan secara film memang selesai, tetapi kan secara masalah tidak selesai. Artinya, kalau banyak yang mengamini bahwa Bu Tejo yang menang, oh, enggak. Menurutku sebagai pembuat, Bu Tejo tidak menang, itu karena tidak ada yang memvalidasi semua omongan Bu Tejo.
Bu Tejo pun sebenarnya keliru, Yu Ning pun akhirnya keliru juga. Sementara Dian, Dian bukan tokoh yang menurutku bisa disalahkan karena dia punya pilihan atas hidupnya sendiri itu tadi. Jadi, itu, sih. Kebanyakan netizen Indonesia begitu kan, mbak. Hal-hal yang ironi tetapi menurut mereka menarik. Mungkin mereka refleksi sendiri kali, ya.
Lalu, ketika ada Bu Tejo, Yu Ning, sama Yu Sam di situ ada perdebatan. Apakah ada nilai female rivalry pada scene tersebut? Sekarang kan di antara perempuan ada juga yang ingin menjadi paling benar. Atau di situ memang cuma gambaran aja kalau kebiasaan ibu-ibu niliki seperti itu?
Sebenarnya dua-duanya termasuk, sih, karena memang di situ ada peran-peran sidekick pendukung Bu Tejo, ada yang kontra sama Bu Tejo dan ada yang netral dan ada juga yang cuek. Cuma memang di dalam sebuah bak truk itu, orang sebenarnya sudah muak dengan Bu Tejo tetapi Bu Tejo karena punya power yang besar, kuasa yang besar, ya dia mencoba untuk berpolitiksasi sebenarnya untuk mendoktrin orang-orang di bak truk itu, akhirnya nanti bisa pro sama dia untuk jadi lurah, menggantikan bu lurah sebelumnya.
Kalau dideskripsikan, nih. Dari Mas Wahyu sendiri menilai film Tilik adalah film komedi kah atau seperti apa?
Drama komedi kali ya, mbak. Sebenarnya begini, kalau komedi, aku enggak tahu responsnya mbak melihat filmnya sendiri bagaimana. Cuma kalau ditelaah lagi, aku sebenarnya tidak ada membuat film itu benar-benar komedi yang mengkomedikan. Artinya, itu kan sebenarnya lucu karena memang tingkah aslinya mereka yang lucu. Bukan aku yang melucu-lucukan, sebenarnya begitu kan.
Jadi, memang orang melihat fenomena itu tuh lucu dan mungkin merefleksi. Akhirnya menjadikan film ini menjadi film yang lucu. Padahal kalau kita telaah lagi, di ending kan bahkan drama banget filmnya kan. Jadi, lebih ke drama, sih, sebenarnya. Komedi itu jadi bumbunya aja.
Lalu, ketika setelah menonton film Tilik, saya juga menonton film Anak Lanang. Nah, yang menarik dari pemyutradaraan Mas Wahyu menggunakan one take long shot. Dari metode itu menjadi trademark Mas Wahyu atau Mas Wahyu nyaman dengan metode seperti itu untuk menceritakan kisah-kisah?
Kalau dibilang trademark enggak juga, mbak. Itu baru satu film yang aku bikin long take juga karena kebetulan waktu itu temenku anak ISI Yogyakarta dia mau tugas akhir. Aku bantu dia dan kebetulan tugas akhirnya mayornya sinematografi dan ambil teorinya soal one take. Kalau dibilang trademark enggak juga, sih.
Cuma memang aku punya, apa ya, treatment sendiri ketika bikin film yang aku rasa, film-film yang pernah aku buat itu kan sebenarnya film-film sederhana. Tidak muluk-muluk, sederhana, dan dari situlah aku berangkat ke teknis-teknis yang lain. Ketika ceritanya sederhana, filmnya sederhana, teknisnya juga menurutku harus sederhana. Jangan sampai gambar memperkosa ceritanya juga.
Kalau ditelaah mungkin aku enggak membuat film yang akhirnya sinematik atau pakai drone lah mungkin, enggak. Menurutku enggak penting. Yang penting ceritanya bahwa elemen-elemen yang lain mendukung aja. Ketika kosepnya memang sederhana ya semuanya juga ikut sederhana. Itu termasuk di film Anak Lanang juga. Ah, hampir semua film pendek yang pernah aku buat begitu, sih.
Ada perbincangan kenapa enggak pakai bis tapi kok truk? Nah, ketika di Yogyakarta memang tradisi orang-orang di sana memakai truk atau seperti apa, sih?
Pada kenyataannya pakai truk, sih, mbak. Sebenarnya ada tiga jenis kendaraan: pick up, truk, bis. Cuma, pada basic-nya ketika aku tanya sama orang-orang sana, mereka itu lebih suka naik truk karena kalau mereka naik bis mereka akan mual, muntah-muntah. Mabuk darat mereka. Dan menurutku truk menjadi medium yang seksi ketimbang pick up sama bis itu diekspos.
Sampai detik ini, di daerah Bantul sana ya, itu masih, masih sering dijumpai orang-orang naik truk yang kalau dilihat realita aslinya itu bahkan jumlah di bak truknya lebih banyak. Mereka akan dempet-dempetan. Dan hampir setiap hari itu ada.
Untuk syuting film Tilik berapa lama dari pra produksi sampai pasca-produksi?
Kalau keseluruhannya kurang lebih mungkin 6-8 bulan kali ya dari benar-benar awal sampai akhirlah. Sampai filmnya rilis pada saat itu. Dan untuk hari syutingnya kita empat hari dan kebetulan itu di bulan puasa di 2018.
Dari Mas Wahyu melihat pesan dalam film ini, karena bekerja sama juga dengan Dinas Kebudayaan Yogyakarta, pada saat itu ketika merilis film ini apa yang ingin disampaikan kepada publik?
Narasi yang kami bawa itu ada dua ya, mbak. Yang paling besar. Satu, tentang berita hoaks atau berita-berita sesat bahwa kita sebagai masyarakat harus bisa bijak dan bisa dewasa menyikapi itu. Artinya ketika ada berita yang datang tidak langsung ditelan mentah-mentah, tapi ada filterisasi, ada validasi, baru disebarkan.
Pada saat itu kami juga sangat resah soal itu dan ketika kami hendak membuat film itu, momennya pas mau pilpres. Itu jadi rentan banget kan untuk black campaign segala macam dan doktrin-doktrin di kampung-kampung. Itu narasi besarnya. Baru kedua adalah perempuan ngomongin soal perempuan dan hak perempuan sampai ke status single perempuan itu.
Soal perempuan, saya suka dengan tokoh Bu Tejo. Dari Mas Wahyu sendiri tim Yu Ning dan Bu Tejo pilih mana?
Aduh, aku enggak bisa memilih karena aku yang membuat mereka, mbak. Jadi, teman-teman yang menonton aja yang memilih mau di kubu mana. Aku di kubunya Gotrek ajalah karena aku laki-laki, ya.
Enggak ada kelanjutannya, mas? Banyak yang penasaran sama Pak Lurah.
Wah, ini gila, sih. Banyak yang minta “Ayo lanjut”. Semoga ya setelah ini ada kabar baik entah jadi film panjang, entah jadi series atau apapun. Kami sih berharap benar-benar ada angin segar setelah ini. Tadi, sih, sempat dapat kontak ayolah coba kita propose ke Netflix dan lain-lain. Semogalah, doakan saja, mbak.
Berarti ada harapan film Tilik juga ditayangkan di OTT atau dilanjutkan?
Iya, betul.
Saya setelah dengar ini langsung meng-approve bahwa yang saya tonton itu betul tentang Dian, tetapi apakah Bu Tejo dari perspektif Mas Wahyu sepenuhnya salah?
Enggak menurutku. Semua salah, sih, menurutku. Kecuali Dian, ya. Menurutku Dian enggak salah.
[teks medcomid | foto ravacana]

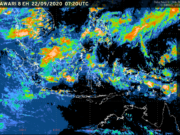




![Cerita di Balik Syuting Petualangan Sherina 2! [NGOBROL BARENG] Cerita di Balik Syuting Petualangan Sherina 2! [NGOBROL BARENG]](https://iradiofm.com/wp-content/uploads/2023/10/Cerita-di-Balik-Syuting-Petualangan-Sherina-2-NGOBROL-BARENG-180x135.webp)