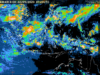Film A Man Called Ahok sukses menuai pujian dan mendapat sambutan positif sejak dirilis beberapa waktu lalu. Putrama Tuta, sutradara yang sebelumnya pernah membuat Catatan Harian Si Boy buka-bukaan, dan berbagi cerita di balik layar.
Bagaimana ia membutuhkan waktu hampir dua tahun untuk proses pembuatan. Dilematis ketika Ahok mendapati berbagai persoalan di sepanjang pembuatan film. Hingga reaksi berlebihan dari publik akan film Ahok yang tak seperti dugaan mereka sebelumnya.
“Pertama kali ketika saya mendapat tawaran bikin film ini, saya ajukan dua syarat yakni menghindari dominasi politiknya, dan memberi sesuatu yang baru, yang orang belum ketahui,” ujarnya saat berbincang di sebuah kafe di Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Seperti apa menggarap film biografi Ahok dan proses pembuatannya? Berikut beberapa jawaban Tuta, yang lugas dan tanpa sensor.
Herworld (HW): Bicara soal ‘A Man Called Ahok’, dari buku ke film. Bagaimana prosesnya?
Putrama Tuta (PT): Film ini diadaptasi dan terinspirasi dari buku Rudi Valinka berjudul sama. Tentu ada pengembangan karakter di dalamnya.
Ceita harus sesuai fakta karena biografi. Namun, karakter di film mengalami pengembangan. Misalkan, karakter Musyono, di buku ada dua Mus dan Yono. Tapi nggak mungkin taruh dua-duanya, karena ini bukan film dengan friendship story tapi father and son.
Makanya jadi Mus. Sementara, di film zero to hero, inspiring movie, ada obstacle, turning point, villain, kalahnya bagaimana. Makanya kemudian ada karakter Rudy yang dimainkan Donny Damara. Penggambaran akan perlawanan, dengan cerita berdasarkan dari buku Rudi.
HW: Ada interview sama keluarga Ahok?
PT: Ada. Sama Ahok, Mbak Fifi, Ibunya, Adiknya Ahok. Saya bahkan tinggal di rumah Ahok. Makan masakan ibu Ahok. Merasakan bagaimana jadi Ahok. Riset sedalam-dalamnya mengenai karakter ayahnya. Kerasnya pak Kin Nam, sifatnya, kenapa ada adegan dia menyepak anak buahnya kalau salah. Keras, tapi semua berdasar riset. Tak mungkin saya bikin ini tanpa dapat persetujuan dari pihak keluarga.
HW: Bagaimana dengan kritik dari adik Ahok, Fifi Lety Tjahaja Purnama, yang sempat ramai di media sosial?
PT: Itu adalah soal sosok. Jadi patut dibedakan bahwa antara ‘karakter’ dan ‘sosok’. Saya tak mungkin dapatkan sosok yang 100 persen mirip ayahnya.
Yang dibahas mbak Fifi, itu aesthetic value, bukan karakternya. Sementara buat saya karakter pak Kin Nam sudah sangat indah sehingga sekarang ada pahlawan baru bernama pak Kin Nam yang tak pernah kita ketahui sebelumnya.
Saya pilih pemeran Chew Kin Wah sebagai Kin Nam, karena dia bisa deliver cerita dengan baik. Pertmbangannya, daripada mirip tapi ceritanya tak sampai, justru pada akhirnya menghancurkan karakter beliau.
Di samping itu, film ini berjudul ‘A Man Called Ahok’, bagaimana cara ayah didik anak laki-lakinya. Tentu berbeda, dengan cara dia mendidik anak perempuan. Jadi, saya ambil dari point of view nya Ahok, sesuai judul film. Tentu saya tak bisa menyenangkan banyak orang, dan seorang ayah juga pasti mendidik anaknya berbeda-beda.
HW: Bagaimana proses pembuatannya dari awal?
PT: Film ini tak pernah direncanakan untuk rilis sekarang. Kita sudah mulai sejak Februari 2017, saat Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Waktu itu banyak sekali yang mendorong Rudi Valinka filmkan bukunya.
Lalu, film ini jatuh ke tangan saya. Menurut Rudi, saya 11-12 karakternya sama Ahok jadi cocok buat sutradarai. Ini menjawab kekhawatiran daripada film ini dibikin asal, sebab sosok Ahok tak muncul 10-20 tahun sekali. Sosok yang bikin perubahan besar, jadi Rudi ingin film ini serius.
Ada produser datang ingin bikin komedi, atau romance. Dia nggak mau. Saya lalu ajukan dua syarat, yakni pertama, nggak akan sentuh sisi politiknya, kedua, film ini harus menceritakan segala sesuatu yang orang tidak tahu. Begitu masuk Jakarta, orang tahu kiprahnya di Jakarta. Jadi dari awal, saya sudah tahu akan habiskan cerita saat ia jadi Bupati. Zero to Hero, bagaimana kaum minoritas jadi pemimpin negara mayoritas.
Awalnya, film ini direncanakan, kalau Ahok kalah dalam pemilihan kepala daerah sebagai ungkapan perpisahan atau goodbye. Atau kalau dia menang, ini bisa buat selebrasi kemenangan.
Satu hal tak diduga, ia terlibat kasus jerat hukum dan masuk penjara karena itu tak pernah disiapkan. Jadi, bukan anggapan karena Ahok di dalam penjara, lalu bikin film. Ini jauh dari peristiwa itu.
Di luar itu, saya ada pengalaman pribadi. Saya berasal dari keluarga tentara. Suatu kali, saya kabur dari sekolah tentara waktu kecil, dan itu mematahkan hati kakek saya. Karena kemudian saya memilih jadi filmmaker.
Dari kecil sudah jadi cita-cita saya berbuat sesuatu untuk bisa membanggakan kakek yang sudah saya patahkan hatinya begitu kesempatan ini datang saya bicara pada Ilya Sigma, istri saya ‘Ini kesempatannya’. Tapi, saya nggak mau attach pada berbau poliik.
Ia bilang, “Sejarah itu ditulis sekarang. Filmmaker berjuang. Bikin filmnya, tidak usah pikir yang lain. Bikin yang bagus. Itu saja.’
HW: Bagaimana respons Ahok?
PT: Ahok tahu dan senang begitu tahu film ini dibuat. Untungnya, kita semua semangatnya sama. Itu yang bikin senang. Saat bikin film Ahok, kita semua tahu ini tak mudah. Banyak kutipan dari pengalaman-pengalaman pribadi yang kemudian dituang di film.
Tapi, kalau cerita harimau itu (kisah yang disampaikan ayah Ahok di meja makan-red) cerita beneran. Fakta yang ditarik. Riset dan komunikasi buat film ini. Buat kami, Ahok sosoknya saja sudah berkonfilk. Banyak yang sayang, juga banyak yang benci.
Salah kalau ada orang beranggapan saya mendramatisir, karena cukup difillmkan saja. Saya jaga struktur dramaturgi, bagaimana bawa emosi penonton dalam film.
HW: Bagaimana prosesnya, dari skrip bangun story?
PT: Kita develope story bareng-bareng. Yang nulis saya, skrip kita riset sama-sama, Teddy Andhika tim riset. Mas Jujur Prananto turut jaga cerita. Saya nulis bersama Ilya Sigma, dibantu Danny Jaka Astrada, juga bersama Rudi Valinka tentunya.
HW: Sejak penayangan hari pertama 8 November lalu, ada reaksi berlebihan atau negatif?
PT: Dari awal, saya yang utama filmnya bagus. Kalau dari saya, literally apa reaksi negatif atau berlebihan di luar, saya tak begitu peduli. Yang penting filmnya bagus, karena ini hidup saya.
Jangan sampai anak saya, melihat saya bikin film ini karena ‘harus’. Buat saya, ini adalah ‘legacy’ yang saya tinggalkan buat anak-anak saya, makanya di tiap film sepenting itu.
Kebetulan, saya dapat pendidikan film yang beruntung. Kayak saya, Timo Tjahjanto, Mouly Surya, sutradara film angkatan terakhir yang belajar untuk bikin film by frame. Ini artinya, kenapa frame harus di atas, kenapa di bawah sangat diperhatikan, karena dulu pakai film itu mahal banget. Begitulah betapa pentingnya setiap frame yang ada. Beda dengan yang digital yang bisa diulang dan dihapus dengan mudah.
HW: Ada reaksi negatif mengkaitkan dengan film lain yang bernuansa politik?
PT: Saya tak begitu ambil pusing akan itu, karena sebenarnya bikin film itu yang penting bagus. Dari awal waktu bikin film Ahok, saya harap yang suka Ahok akan nonton. Tapi bukan berharap hanya Ahokers yang nonton. Makanya ceritanya merupakan cerita keluarga.
Pada dasarnya, saya selalu ingin bikin film berdampak bagi penonton. Salah satu yang real, yang membuat hati seolah disiram air es. Sebagai orangtua, ayah dari dua anak perempuan, saya selalu berpikir bagaimana memberi nilai pada anak-anak tapi bukan yang preachy atau ‘ngajarin’.
Banyak orangtua yang habis nonton film ini, bilang terima kasih karena tak perlu lagi ngomong jadi bisa kesampaian bilang apa sama anak-anak mereka.
Karenanya, film ini tak hanya untuk Ahoker saja, tapi dibuat untuk generasi penerus bangsa supaya mereka jadi orang jangan abu-abu. Mau hitam ya hitam, putih ya putih. Jangan di tengah- tengah bimbang mau ngapain berani bersuara, berbuat sesuatu. Ini yang perlu bikin bangsa ini jadi lebih baik.
Di luar itu, saya ingin bikin bahagia kakek, yang dulu pernah dipatahkan hatinya saat saya keluar dari sekolah militer. Dia belum nonton, tapi dengar impact dari orang yang sudah nonton, lalu bilang, ‘prestasi kamu ini mau dibawa ke mana?’. Sementara nenek saya, usai menonton premier, pegang tangan saya dan bilang ‘ini cucu saya’. Dan itu sudah bikin saya bangga.
HW: Kenapa menghindari politik?
PT: Karena menurut saya nggak perlu, karena dengan begitu akan menjadi justifikasi. Saya ingin bikin film yang orang belum tahu. Goal-nya pengen bikin bangsa jadi lebih baik, banyak orang bersuara, dan bersikap. Jadi dari awal, saya memang tak mau sentuh politik.
Sumber Her World Indonesia

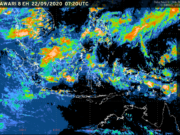




![Cerita di Balik Syuting Petualangan Sherina 2! [NGOBROL BARENG] Cerita di Balik Syuting Petualangan Sherina 2! [NGOBROL BARENG]](https://iradiofm.com/wp-content/uploads/2023/10/Cerita-di-Balik-Syuting-Petualangan-Sherina-2-NGOBROL-BARENG-180x135.webp)